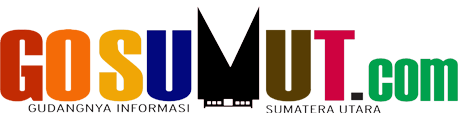SAYA terdiam menemukan laman di Google, yang mengabarkan Prof. Stuart Loory sudah meninggal dunia sejak awal 2015 lalu. Dia adalah guru besar di sekolah jurnalisme tertua dunia di Missouri University, Amerika Serikat.
Prof Loory pernah menyambut saya dengan diskusi hangat tentang jurnalisme dan media sewaktu berkunjung ke kampusnya sekitar Agustus 2001. Saat itu saya beruntung masuk menjadi peserta dalam program International Visitor for Journalist ke Negeri Paman Sam. Kami mendiskusikan tentang kehidupan pers bebas namun mengemban tanggungjawab di negerinya dan dunia. Seolah tak ada cela, Prof Loory amat membanggakan kebebasan pers di negerinya, yang kemudian ditiru oleh banyak negara di dunia. Tapi dia agak kaget saat saya menyela bahwa jurnalis dan media di negerinya tidak sejak awal menjalankan konsep kebebasan pers demikian, karena sejarah mencatat kapitalisme sempat menunggangi kebebasan pers yang sangat liberal di sana. Masa itu siapapun yg ingin menggunakan ruang berita mesti membayar, tarifnya tergantung luas space dan kolom yang digunakan. Mirip iklan, padahal berita sesungguhnya jiwa idealisme pers, tidak bisa diperjualbelikan bak iklan. Kepentingan kapitalisme yg mengabaikan sisi idealisme media itu akhirnya diprotes karena mempersulit masyarakat mengadukan aspirasinya untuk kepentingan yang lebih luas. Kepercayaan publik pun sempat menurun terhadap pers masa itu. Kondisi itu kemudian dianggap membahayakan, mengingat pers adalah lembaga kepercayaan yang berarti hanya bisa hidup dari kepercayaan yang diberikan oleh publik. Bayangkan, seandainya masyarakat ogah mengonsumsi berita dari media karena sdh tak mempercayainya lagi, pasti tiras atau rating turun dan iklan pun tak akan masuk lagi. Maka "monding" atau tamatlah lah media tersbut. Makanya, kata saya menyambung cakap, akhirnya dibentuklah Komisi Hutchins di tahun 1940-an yang dipimpin Robert Hutchins untuk mengevaluasi sistem pers liberal yang dianggap sudah tak akomodatif terhadap publik. Hasilnya, komisi ini menawarkan sistem pers dlm konsep "responsibility of journalism" kepada Paman Sam. Konsep ini memberikan kebebasan kepada pers tetapi mesti berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab menguraikan permasalahan publik. Prof Stuart Loory mengernyitkan kening mendengar cakap saya. Namun kemudian dia tersenyum membenarkan. "Well, ternyata Anda mengetahui pasang surut kebebasan pers di AS, " katanya. Sejak itu kami sempat akrab dan beberapa kali saling berkirim email sesampainya saya kembali di tanah air. Bahkan dia pernah menawari saya program beasiswa pasca sarjana di kampusnya. Saudara-saudara, sejatinya konsep "responsibility of journalism" itulah yang digunakan AS dewasa ini setelah meninggalkan sistem pers liberal. Eh, sebaliknya banyak media di Indonesia justru cenderung menerapkan sistem pers yang sudah ditinggalkan Paman Sam meski mengaku-aku mengusung sistem pers bertanggungjawab pula. Lihat saja, banyak berita tidak boleh disiarkan, bukan karena tidak berkorelasi dengan kepentingan publik, melainkan karena narasumber dan institusinya tidak beriklan di media-media tersebut. Tapi ada pula peristiwa tak begitu penting bagi publik mesti ditayangkan karena melibatkan pemasang iklan didalamnya. Kepentingan bisnis sangat kuat mengintervensi newsroom dalam menurunkan berita. Kebebasan pers yang bertanggungjawab pun terganggu seiring melunturnya independensi redaksi. Kalau berlarut-larut, bukan mustahil kepercayaan publik juga bakal menipis terhadap media kita. Ujung-ujungnya, tentu akan membahyakan keberlangsungan hidup pers di negeri ini. Kesimpulan tersebut mengemuka lagi pagi ini, setelah saya diam berduka menemukan kabar Prof Stuart Loory berpulang di laman Google. Mantan wartawan Los Angeles Times, CNN, dan sejumlah media besar lain itu meninggalkan kenangan bernas buat saya. Bye, Prof Loory... *Penulis adalah wartawan, pemimpin redaksi GoSumut.comJum'at, 10 Sep 2021 08:46 WIB
Kolom: Stuart Loory, Paman Sam, dan Pers Indonesia

| Editor | : | Ari |
| Kategori | : | Kolom, Tokoh |