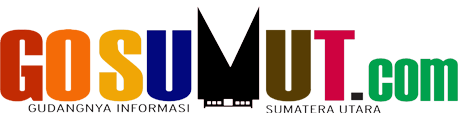SEORANG pelancong Inggris, John Anderson, tiba di Deli pada 1833, dan menemukan sebuah kampung bernama Madaan Putri. Kata pertama dari nama itu berarti menjadi sehat atau lebih baik, dalam bahasa Karo. Penduduknya sekira 200-an orang.
Dipimpin tokoh bernama Raja Pulau Berayan. Ia menarik pajak dari sampan-sampan pengangkut lada yang menyusuri delta Sungai Deli dan Baburah.
Dalam Riwayat Hamparan Perak yang dokumen aslinya ditulis dengan huruf Karo pada rangkaian bilah bambu, tercatat Guru Patimpus Sembiring Pelawi, tokoh masyarakat Karo, sebagai orang yang pertama kali membuka kampung itu.
Patimpus adalah anak Tuan Si Raja Hita, pemimpin Karo yang mukim di Kampung Pakan. Ia menolak menggantikan ayahnya dan lebih tertarik pada ilmu pengetahuan dan mistik, sehingga akhirnya dikenal sebagai Guru Patimpus.
Antara 1614-1630 Masehi, ia mendalami Islam dan kemudian memeluknya di bawah arahan Datuk Kota Bangun—setelah kalah dalam adu kesaktian. Guru Patimpus inilah yang berperan sebagai pembabat alas kampung Madaan pada 1 Juli 1590.
Kini, nama tersebut lambat laun berubah menjadi Medan, dengan jumlah penduduk 4.744.323 jiwa, dan luas wilayah 265,1 km². Kita kembali ke tempo dulu. Setengah abad berjarak dari kedatangan John, tepatnya pada 1886, Medan secara resmi memeroleh status sebagai kota, dan setahun berselang menjadi ibukota Karesidenan Sumatera Timur sekaligus ibukota Kesultanan Deli.
Memasuki medio 1909, Medan menjadi kota penting di luar Jawa, terutama setelah kolonial Belanda membuka perusahaan perkebunan secara massal. Dewan kota yang pertama terdiri dari 12 anggota orang Eropa, dua orang bumiputra Melayu, dan seorang Tionghoa. Pada era inilah muncul sebuah julukan, Paris van Suwarnadwipa.
Sebagai Putra Deli yang lama bermukim di Jakarta, kami tak henti mengamati pertumbuhan kota legendaris ini secara seksama. Membuncah jua kebanggaan saat mengetahui betapa Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta apinya.
Kualanamu juga tercatat sebagai bandar udara terbesar kedua setelah Sukarno-Hatta. Tak hanya itu. Kota penghasil teh terbaik ini, masuk jajaran terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya.
Wajar bila kemudian di sini ada sembilanbelas konsulat jenderal yang mewakili Amerika Serikat, Australia, Belanda, Belgia, Britania Raya, Tiongkok, Denmark, India, Jepang, Jerman, Malaysia, Norwegia, Pakistan, Rusia, Singapura, Sri Lanka, Swedia, Thailand, dan Turki. Kenapa negara tersebut berkenan mendirikan konjennya di sini?
Tak lain karena, Medan sudah semacam miniatur Indonesia dengan keragaman etnisnya, seperti Melayu, Karo, Batak, Jawa, Minangkabau, Tamil, dan Tionghoa. Kebhinekaan itu bisa dilihat dari jumlah masjid, gereja, dan vihara yang banyak tersebar di seantero kota.
Daerah di sekitar Jl. Zainul Arifin, dikenal sebagai Kampung Keling, yang merupakan wilayah pemukiman orangorang keturunan India.
Hal menarik lain yang mungkin jarang diketahui publik adalah, Medan punya lima kota kembaran di negeri manca. Ada Georgetown di Pulau Penang, Malaysia. Lalu Ichikawa (Jepang), Gwangju (Korea Selatan), Chengdu (Republik Rakyat Tiongkok), dan Milwaukee (Amerika Serikat).
Dengan kata lain, kota kita tercinta ini bisa mengembangkan dirinya bersama kota - kota besar tersebut, dengan terus melakukan pertukaran dalam segala lini peradaban.
Kecuali Georgetown dan Gwangju, tiga kota lain merupakan representasi dari kemajuan negara masing-masing. Paling tidak, masyarakat Medan bisa melakukan proses tranformasi ke arah kemajuan, dengan menjalin hubungan internasional pada penduduk di tiga kota tersebut.
Langkah semacam, bisa menjadi mudah bila difasilitasi pemerintah kota, dengan melibatkan generasi terbaik yang mukim di Medan saat ini. Selama dilakukan secara serius dan sepenuh hati, apa yang kami sampaikan di atas kelak mewujud nyata, dengan hasil yang gilang gemilang.
Kita yang sekarang hidup pada zaman baru, di mana jendela teknologi informasi terbuka lebar, sudah sewajarnya menjalin kontak antarbangsa dengan mudah. Toh ikatan kerjasama sejenis, tak melulu harus dilakukan pemerintah pusat. Malah menjadi keniscayaan bila dikerjakan oleh individu per individu.
Tengoklah media sosial tuh. Siapa saja di belahan bumi mana pun, bisa kita akses hanya dengan bermodal kuota internet. Dunia yang seolah tak lagi bersekat ini, jelas memberi banyak peluang dan tantangan besar.
Nyaris sama dengan Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Semarang, di Medan juga ada pola pemukiman yang mengikuti perluasan kota. Perubahan ini menjadi penanda masyarakat dinamis yang bermukim di dalamnya.
Etnis Melayu yang merupakan penduduk asli, banyak yang tinggal di pinggiran kota seperti Belawan, Denai, dan Marelan. Etnis Tionghoa dan Minangkabau yang sebagian besar menghidupi bidang perdagangan, 75%-nya tinggal di sekitar pusat perbelanjaan.
Pemukiman dua etnis ini, sejalan dengan arah pemekaran dan perluasan fasilitas pusat perbelanjaan. Tak ubahnya orang Melayu, orang Mandailing juga memilih tinggal di pinggiran kota yang lebih nyaman.
Oleh karena itu, terdapat kecenderungan di kalangan mereka untuk menjual rumah dan tanahnya di tengah kota, seperti di Kampung Masjid, Kota Maksum, dan Sungai Mati.
Sedangkan pemukiman orang Karo dan Batak, kebanyakan berada di bagian selatan kota, seperti Simalingkar atau Padang Bulan. Hal tersebut dikarenakan jarak antara Medan wilayah selatan lebih dekat dengan kampung halaman mereka, dibandingkan pusat kota maupun wilayah pesisir—khususnya orang Karo yang berdomisili di sekitar Sibolangit, Berastagi, dan Kabanjahe. Karena mereka hanya tinggal mengikuti Jalan Raya Jamin Ginting terus ke arah selatan.
Tipologi tersebut sejatinya bisa dijadikan keunggulan tersendiri. Jika pemkot berkenan, misalnya, basis kebudayaan mereka sangat mungkin dikembangkan ke arah yang jauh lebih serius. Bukan hanya sekadar mendirikan rumah adat, melainkan menghidupkan marwah budayanya.
Sebagai contoh. Bangunlah sebuah universitas dengan fakultas khusus bisnis serta turunannya. Jadikan para pengusaha Minang dan Tionghoa sebagai dosen tamu. Tahbislah mereka menjadi profesor atau bahkan doktor honoris causa, sebagaimana yang sudah diterima Tumpal Dorianus Pardede.
Becermin dari Shenzen
Selaku ibukota provinsi Sumatera Utara, Medan yang pernah disaksikan Chairil Anwar dan Cong A Fie, perlu belajar banyak dari pemerintah kota Shenzen, yang mulai dibangun pada 26 Agustus 1980.
Dalam empat dekade ke belakang, kota ini mekar menjadi kosmopolit dijital, dengan klaim sebagai The Silicon Valley of Asia. Dulu, kota modern ini dibangun di lokasi pemukiman nelayan yang kumuh. Jikalau melihat fotonya sebelum reformasi kota pada 1980, Shenzen hanya semacam desa besar.
Tapi semua itu berubah 180 derajat menjadi kota megalopolitan, berkat pemimpin dan manajemen yang cerdas. Dengan proses perubahan modernisasi yang begitu cepat, sudah tentu Gross Domestic Product kota ini meningkat cepat.
Peningkatannya sedari 1980 sampai sekarang diperkirakan 10.000 kali lipat. Shenzhen tidak lagi diberi subsidi oleh pemerintah pusat. Sehingga harga barang lebih mahal jika dibanding dengan Nanning dan kotakota lain di wilayah selatan China. Harga disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.
Bagi yang tidak siap bersaing, tidak memiliki pola pikir maju, takkan mampu bertahan di kota ini. Mereka yang siap tinggal di sini, hanya pemiliki kreativitas dan semangat hidup tinggi.
Bagi yang hidupnya masih bergantung pada subsidi, pemerintah Tiongkok juga sudah menyediakan wilayah lain sesuai kapasitas mereka. Mentalitas penduduk Shenzhen sangat hebat, patut ditiru. Kota yang semula meniru pengembangan Batam, hasil prakarsa mantan Presiden BJ. Habibie, kini malah melampaui Jakarta. Kendati hanya sebuah subkota dari provinsi Guangdong. Sementara Batam, sejauh ini cuma sanggup menjadi persinggahan barang elektronik dari luar Indonesia, yang cenderung mengarah ke pasar gelap. Sebenarnya, pembangunan awal Shenzhen juga sempat terhenti. Pemerintah China sudah berinvestasi banyak, namun tetap tidak bisa sejajar dengan Hong Kong. Penanaman modal pun seolah sia-sia. Alhasil ditunjuklah semacam BUMN Singapura (pada 1989) sebagai pengelola, sekaligus konsultan pengembangan Shenzen dengan model Free Trade Zone. Dalam waktu singkat, Shenzen sudah mengalahkan Singapura dan Hong Kong. Deng Xiaoping yang sedang memimpin China waktu itu, memang jenius. Ia memilih mendatangkan orang Singapura yang telah terbukti berhasil mengubah negaranya menjadi makmur dan kaya-raya. Bagi Deng, transfer pengetahuan yang dilakukan di negeri sendiri akan lebih mudah, tinimbang mengutus orang Tiongkok belajar ke negeri Singa, untuk kemudian diterapkan di dalam negeri. Singapura hanya diberi hak sepuluh tahun untuk mengelola, selanjutnya, pengelolaan sepenuhnya diambilalih kembali oleh otoritas Tiongkok. Pada saat Shenzhen menjadi kota kosmopolitan, perubahan sosial terjadi secara otomatis di sana. Tiada lagi orang berjalan dengan baju lusuh sambil telanjang dada, meludah sembarangan di jalan, atau buang air di tepi sungai. Tidak ditemukan lagi rumah di pinggir rel kereta, atawa orang berjubelan di dalam bus. Kini mereka berpakaian modern a la masyarakat Barat. Menetap di apartemen bersih dengan sanitasi terjamin. Memiliki sarana publik nan canggih. Kendaraan roda dua di jalanan utama digantikan angkutan massal berkelas dunia. Gaya hidup mereka yang tadinya statis, berubah dinamis dan kreatif. Jika kota berubah, mental warganya, juga rekayasa sosial pun ikut berubah. Kehidupan menjadi lebih baik, lebih apik. Semoga masyarakat Medan, terutama bangsa Indonesia, tidak terus terjebak polarisasi akibat peristiwa politik domestik. Tak lagi meributkan sesuatu yang sumir. Negara lain sudah melaju cepat, sementara kita seolah jalan di tempat. Shenzen telah tumbuh dengan pesat mengalahkan Singapura, Hong Kong, Boston, dan Batam sebagai tetironnya. Padahal misi awal perubahan Shenzhen, ya meniru pengembangan Batam. Orang Indonesia memang jago membuat terobosan baru, tapi soal kerjasama, keberlanjutan, dan perawatan, selalu mengalami masalah. Kenapa demikian? Bukankah kita inilah bangsa yang gemar bergotong-royong? ** Penulis adalah penyintas peradaban dan juga Founder
Yayasan Katulistiwa Muda
Bagi yang hidupnya masih bergantung pada subsidi, pemerintah Tiongkok juga sudah menyediakan wilayah lain sesuai kapasitas mereka. Mentalitas penduduk Shenzhen sangat hebat, patut ditiru. Kota yang semula meniru pengembangan Batam, hasil prakarsa mantan Presiden BJ. Habibie, kini malah melampaui Jakarta. Kendati hanya sebuah subkota dari provinsi Guangdong. Sementara Batam, sejauh ini cuma sanggup menjadi persinggahan barang elektronik dari luar Indonesia, yang cenderung mengarah ke pasar gelap. Sebenarnya, pembangunan awal Shenzhen juga sempat terhenti. Pemerintah China sudah berinvestasi banyak, namun tetap tidak bisa sejajar dengan Hong Kong. Penanaman modal pun seolah sia-sia. Alhasil ditunjuklah semacam BUMN Singapura (pada 1989) sebagai pengelola, sekaligus konsultan pengembangan Shenzen dengan model Free Trade Zone. Dalam waktu singkat, Shenzen sudah mengalahkan Singapura dan Hong Kong. Deng Xiaoping yang sedang memimpin China waktu itu, memang jenius. Ia memilih mendatangkan orang Singapura yang telah terbukti berhasil mengubah negaranya menjadi makmur dan kaya-raya. Bagi Deng, transfer pengetahuan yang dilakukan di negeri sendiri akan lebih mudah, tinimbang mengutus orang Tiongkok belajar ke negeri Singa, untuk kemudian diterapkan di dalam negeri. Singapura hanya diberi hak sepuluh tahun untuk mengelola, selanjutnya, pengelolaan sepenuhnya diambilalih kembali oleh otoritas Tiongkok. Pada saat Shenzhen menjadi kota kosmopolitan, perubahan sosial terjadi secara otomatis di sana. Tiada lagi orang berjalan dengan baju lusuh sambil telanjang dada, meludah sembarangan di jalan, atau buang air di tepi sungai. Tidak ditemukan lagi rumah di pinggir rel kereta, atawa orang berjubelan di dalam bus. Kini mereka berpakaian modern a la masyarakat Barat. Menetap di apartemen bersih dengan sanitasi terjamin. Memiliki sarana publik nan canggih. Kendaraan roda dua di jalanan utama digantikan angkutan massal berkelas dunia. Gaya hidup mereka yang tadinya statis, berubah dinamis dan kreatif. Jika kota berubah, mental warganya, juga rekayasa sosial pun ikut berubah. Kehidupan menjadi lebih baik, lebih apik. Semoga masyarakat Medan, terutama bangsa Indonesia, tidak terus terjebak polarisasi akibat peristiwa politik domestik. Tak lagi meributkan sesuatu yang sumir. Negara lain sudah melaju cepat, sementara kita seolah jalan di tempat. Shenzen telah tumbuh dengan pesat mengalahkan Singapura, Hong Kong, Boston, dan Batam sebagai tetironnya. Padahal misi awal perubahan Shenzhen, ya meniru pengembangan Batam. Orang Indonesia memang jago membuat terobosan baru, tapi soal kerjasama, keberlanjutan, dan perawatan, selalu mengalami masalah. Kenapa demikian? Bukankah kita inilah bangsa yang gemar bergotong-royong? ** Penulis adalah penyintas peradaban dan juga Founder
Yayasan Katulistiwa Muda