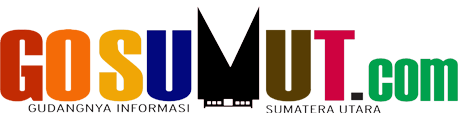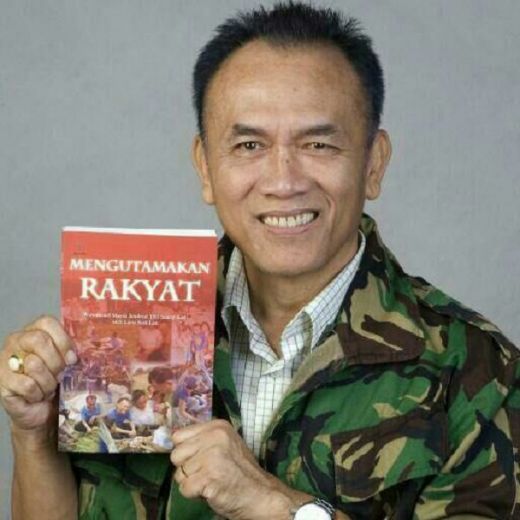NORMA Threshold awalnya hanya dikenal dalam sistem parlementer. Hal ini terkait dengan model Pemilu yang dilaksanakannya, dimana Rakyat dalam Pemilu mencoblos Tanda Gambar Partai. Artinya, yang dipercaya Rakyat adalah Partai, maka anggota DPR adalah Wakil Partai dan di DPR dikenal ada suara Partai. Oleh karenanya, maka setiap Partai harus menempatkan wakilnya disemua lembaga alat kelengkapan DPR yaitu Fraksi, Komisi-Komisi, Banggar, dan lain-lainnya. Jumlah minimal perolehan kursi yang dibutuhkan agar sebuah Partai bisa menempatkan wakil pada semua alat kelengkapan DPR tersebut dikenal dengan istilah Parlementary Threshold.
Sementara itu, pada sistem presidensial, dalam Pemilu rakyat mencoblos tanda gambar orang. Artinya yang dipercaya rakyat adalah orang, bukan Partai. Karena legitimasi Presiden dan Anggota DPR datangnya langsung dari rakyat, maka mereka tidak bisa dicopot ditengah jalan, kecuali karena alasan pidana.
Sementara itu kedudukan Presiden disamping sebagai Kepala Negara juga sebagai Kepala Pemerintahan, disisi lain, Anggota DPR adalah sebagai Wakil Rakyat bukan Wakil Partai, maka di DPR tidak dikenal Suara Partai. Sudah barang tentu dalam Pilpres dan juga dalam membentuk DPR juga tidak dikenal norma Threshold. Dan Pilpres dilaksanakan lebih dahulu, baru disusul Pilleg.
Perancis, belakangan menemukan model campuran, diamana Kepala Negara dengan sebutan presiden tidak lagi berdasarkan keturunan, tapi dipilih melalui Pemilu dengan model presidensial. Dan dalam pembentukan pemerintahan ditempuh melalui Pemilu dengan model Parlementer.
Mengingat Presiden tidak mempunyai hak sejarah atas negara, maka untuk mengantisipasi terjadi kekosongan kekuasaan pemerintahan akibat Perdana Menteri "jatuh", maka dalam membentuk kabinet baru Presiden perlu dukungan politik dari DPR. Disanalah maka dikenal istilah Presidensial Threshold yaitu jumlah minimal Anggota DPR dari Partai atau Gabungan Partai untuk bisa mengajukan Calon Presiden.
Dari logika politik yang demikian itu, maka dalam sistem demokrasi campuran model Perancis dikenal norma Presidensial maupun Parlementary Threshold. Lantas, bagaimana dengan sistem kenegaraan kita?
Dengan Pemilu Serentak, Threshold Dihapus. Demokrasi kita semrawut, tak terkecuali soal Pemilu. Lihat saja Pemilu Legislatif 2004, 2009 dan 2014 dimana ada dua tahap, yaitu Pilleg dan Pipres. Apa dasar bagi rakyat untuk menjatuhkan pilihan dalam Pileg ?. Bila alasannya adalah memilih program partai, sudah barang tentu itu bohong, karena yang dijadikan program kerja pemerintah program sang Calon presiden pemenang Pemilu, sama sekali bukan program Partai.
Karena Pilleg dilaksanakan duluan, maka Partai belum mempunyai Calon Presiden definitif. Pertanyaannya, siapa sosok Capres yang akan diajukan oleh masing-masing Partai? Artinya, Rakyat disuruh tanda tangan cek kosong, kemudian diserahkan kepada partai untuk "dagang sapi" dalam mencari Capres. Maka, wajar saja kalau partai-partai terlibat dalam "politik uang" untuk mendapatkan harga tawar yang tertinggi dari para Calon Presiden.
Terhadap kejanggalan diatas, MK sudah bertindak benar yaitu dengan Putusan Pemilu serentak, sehingga norma presidensial threshold menjadi tidak relevan lagi. Sangat disayangkan terobosan tersebut menjadi sia-sia, ketika MK kembali menolak Uji Materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017. Hal tersebut tidak bisa lepas dari kelemahan model MK di kita yang sumber Hakim nya dibatasi hanya dari Sarjana Hukum. Berbeda dengan MK dikebanyakan negara, sumber hakimnya diambil dari ahli dari semua cabang pokok disiplin ilmu. Sehingga validitas keahlian sebagai penguji Yudicial Review UU apapun dapat dipertanggung jawabkan.
MK Tonggak Tata Negara. Dengan mengandai Presiden Jokowi akan kembali maju sebagai Capres dan menang dalam Pilpres 2019, sangatlah tidak masuk akal kalau Presiden Jokowi berkepentingan melanjutkan norma Presidensial Threshold, karena kemenangannya akan membuat dirinya kembali terbelenggu relitas politik dan terus akan menjadi bulan-bulanan pihak-pihak bermasalah. Sedangkan bicara kendaraan politik, selaku incumben justru akan banyak Partai Peserta Pemilu yang "meminang" nya. Sementara itu, alasan mengesampingkan sementara kebenaran, etika dan moral demi kepentingan yang lebih besar juga tidak relevan, karena sejatinya yang tidak siap untuk berdemokrasi itu elitnya, sama sekali bukan Rakyat nya. Hal ini terbukti dalam Pilkada serentak yang baru saja kita laksanakan, ternyata aman dan terkendali. Dengan demikian MK semestinya mempertimbangkan dengan sungguh- sungguh bahwa norma Presidensial Threshold tidak boleh digunakan sebagai alat filtering, karena otomatis akan mendistorsi dan menihilkan makna kedauatan rakyat, sekaligus melanggar HAM. Sehingga kelak untuk Pemilu 2024, penyusun UU akan memilih "alat" yang sah menurut hukum, seperti memperberat persyaratan bagi Partai untuk bisa ikut Pemilu. Karena dengan syarat Kepengurusan Partai sebesar 100% di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan saja, maka jumlah Peserta Pemilu tidak akan lebih dari 3 Partai. Dengan menghilangkan norma Presidensial Threshold, maka kelak presiden terpilih tidak lagi terkooptasi “pemilik” Partai, dan sekaligus praktek kartel dan oligharky kekuaasaan juga akan berakhir. Kini nasib demokrasi kita ada ditangan Para Hakim MK sebagai tonggak (referensi) tata negara yang rasional dan sistemik. Apakah MK akan konsisten dengan Putusan “Pemilu Serentak” yang secara keilmuan berarti tanpa Presidensial Threshold. Atau sebaliknya, malah mengesahkan upaya pendistorsian dan penyelewengan jiwa, semangat dan amanat UUD melalui UU turunannya. Oleh karenanya maka MK jangan PLIN-PLAN. Penulis: Mayjen TNI (Purn), Mantan Anggota Komisi - II/DPRRI.
MK Tonggak Tata Negara. Dengan mengandai Presiden Jokowi akan kembali maju sebagai Capres dan menang dalam Pilpres 2019, sangatlah tidak masuk akal kalau Presiden Jokowi berkepentingan melanjutkan norma Presidensial Threshold, karena kemenangannya akan membuat dirinya kembali terbelenggu relitas politik dan terus akan menjadi bulan-bulanan pihak-pihak bermasalah. Sedangkan bicara kendaraan politik, selaku incumben justru akan banyak Partai Peserta Pemilu yang "meminang" nya. Sementara itu, alasan mengesampingkan sementara kebenaran, etika dan moral demi kepentingan yang lebih besar juga tidak relevan, karena sejatinya yang tidak siap untuk berdemokrasi itu elitnya, sama sekali bukan Rakyat nya. Hal ini terbukti dalam Pilkada serentak yang baru saja kita laksanakan, ternyata aman dan terkendali. Dengan demikian MK semestinya mempertimbangkan dengan sungguh- sungguh bahwa norma Presidensial Threshold tidak boleh digunakan sebagai alat filtering, karena otomatis akan mendistorsi dan menihilkan makna kedauatan rakyat, sekaligus melanggar HAM. Sehingga kelak untuk Pemilu 2024, penyusun UU akan memilih "alat" yang sah menurut hukum, seperti memperberat persyaratan bagi Partai untuk bisa ikut Pemilu. Karena dengan syarat Kepengurusan Partai sebesar 100% di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan saja, maka jumlah Peserta Pemilu tidak akan lebih dari 3 Partai. Dengan menghilangkan norma Presidensial Threshold, maka kelak presiden terpilih tidak lagi terkooptasi “pemilik” Partai, dan sekaligus praktek kartel dan oligharky kekuaasaan juga akan berakhir. Kini nasib demokrasi kita ada ditangan Para Hakim MK sebagai tonggak (referensi) tata negara yang rasional dan sistemik. Apakah MK akan konsisten dengan Putusan “Pemilu Serentak” yang secara keilmuan berarti tanpa Presidensial Threshold. Atau sebaliknya, malah mengesahkan upaya pendistorsian dan penyelewengan jiwa, semangat dan amanat UUD melalui UU turunannya. Oleh karenanya maka MK jangan PLIN-PLAN. Penulis: Mayjen TNI (Purn), Mantan Anggota Komisi - II/DPRRI.