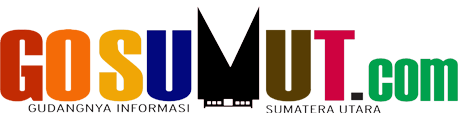MEDAN-Masyarakat Sumatera Utara memiliki banyak seni pertunjukan tradisional. Ada Opera Batak pada masyarakat Batak (Toba). Ada Teater Bangsawan (Melayu) Opera China (etnis Tionghoa) dan ada juga Ketoprak Dor (etnis Jawa-Sumatera).
Ketoprak Dor adalah seni tradisi yang menggabungkan musik tari dan lakon. Kesenian ini merupakan warisan di zaman kuli kontrak atas orang-orang Jawa di Tanah Deli, Sumatera Timur. Kesenian ini merupakan bagian dari sejarah perbudakan kuli kontrak di masa kolonial Belanda yang menguasai perkebunan tembakau di daerah ini, pada akhir abad ke-19 M. Seperti tercatat dalam berbagai sumber sejarah, hanya dalam kurun waktu 25 tahun (1900-1925) telah terjadi konversi lahan atas satu juta hektar hutan di Sumatera Timur untuk dijadikan perkebunan tembakau dan karet. Hal itu juga diungkap ahli sejarah Asia Tenggara, Anthony Reid dalam dalam pengantarnya di buku Tropic Fever: The Adventure of a Planter in Sumatra (1989), karya Ladislao Szekely. Disebutkan dalam buku itu, saat itu tembakau Deli memasok nyaris separuh kebutuhan tembakau dunia. Untuk pekerjanya Belanda mendatangkan tenaga pekerja dari Jawa sebagai pekerja “kasar” dan pekerja dari China untuk ahli tanam. Kedatangan imigran kuli itu membuat penduduk Medan bertambah berkali lipat. Tercatat pada 1880, penduduk di sekitar Medan hanya 120.000, setelah kedatangan kuli kontrak itu bertambah menjadi 1.197.000 orang. Kolonial Belanda bergelimpangan uang dari hasil ekspor dua komoditi itu. Mereka mulai membangun kantor-kantor untuk mengendalikan pemasaran tembakau Deli dan karet itu. Lewat tembakau Deli dan karet, Belanda menguasai pasar dunia. Tidak terkira uang hasil ekspor tembakau Deli dan karet itu. Namun tidak demikian dengan nasib para kuli kontrak. Kehidupan ekonomi mereka justru semakin sengsara. Mereka harus mengalami penindasan, penyikasaan fisik dan mental. Siksaan yang mereka alami tidak terkira. Tenaga mereka diperas dan mereka hidup dalam kungkungan. Hal itu karena mereka terikat dengan UU Ordonansi Kuli 1880. Jika dalam masa kontrak itu mereka mencoba melarikan diri, mereka akan diburu, ditangkap, dihukum dengan cara keji. Kekejian itu tidak hanya dilakukan oleh kolonial, juga mandor-mandor yang direkrut dari masyarakat pribumi. Seperti pernah dijelaskan wartawan senior, Idris Pasaribu. Ia melakukan riset untuk bukunya “Acek Botak”. Buku ini mengisahkan sejarah imigrasi masyarakat China ke Medan dan menceritakan penderitaan kuli kontrak. Salah satunya mengisahkan kekejaman mandor-mandor lapangan. Kadang mereka lebih kejam dari pegawai Belanda. Mereka tak segan menganiaya pekerja itu. Yang perempuan kerap mendapat pelecehan seksual. Karena penderitaan yang terus menerus serta kemiskinan yang semakin parah, membuat sebagian kuli kontrak ini memilih jalan pintas. Salah satunya dengan “menjual” anak gadisnya kepada mandor-mandor. Jika beruntung anak gadisnya itu dipersunting pegawai Belanda. Tak perduli sekalipun hanya dijadikan istri simpanan. Menghibur Diri Hidup dalam penindasan dan siksaan, para kuli kontrak itu hanya bisa membayangkan kampung halaman mereka di Jawa. Pada waktu-waktu tertentu mereka berkumpul dan bercerita tentang kampungnya masing-masing di Pulau Jawa. Untuk bisa saling menghibur mereka kemudian menggelar pertunjukan seni tradisi. Hal itu mereka lakukan secara diam-diam. Mereka mengadopsi seni ketoprak dari Jawa. Pertunjukan itu kemudian dikenal dengan sebutan Ketoprak Dor. Lewat pertunjukan Ketoprak Dor itulah mereka menumpahkan kesedihan, kegelisahan dan keputusasaan atas nasib buruk yang mereka terima di Tanah Deli. “Ketoprak Dor lahir dari penderitaan para imigran Jawa yang bekerja sebagai kuli kontrak di Sumatera Timur. Melalui seni pertunjukan ini mereka lampiaskan kesedihan mereka. Lewat kesenian inipula mereka bisa tertawa. Dengan kata lain, Ketoprak Dor lahir dari rahim penderitaan para kuli kontrak,” jelas pegiat Ketoprak Dor dari Komunitas Je De, Yono USU. Yono yang pernah menjadi dosen luar biasa di Universitas Nommensen dan USU ini menjelaskan perbedaan Ketoprak Dor dengan ketoprak yang dari Jawa. Kalau ketoprak Jawa, khususnya peninggalan budaya Mataram, menggunakan ensambel gong dan gamelan. Sedangkan Ketoprak Dor tidak menggunakan gong, tetapi tanjidor. Karena itulah disebut Ketoprak Dor. Ketoprak Dor lebih bersifat opera. Sisi dramanya lebih kuat dibanding ketoprak dari Jawa. Seiring waktu bersamaan dengan hengkangnya Belanda dari Indonesia, para kuli kontrak itu mulai mendapatkan kebebasannya. Perlahan-lahan Ketoprak Dor pun tak lagi mereka pentaskan. Hal itu dilakukan dengan sadar karena Ketoprak Dor dinilai hanya akan mengingatkan mereka akan nasib buruk selama menjadi kuli kontrak. Rasa trauma yang berkepanjangan membuat mantan kuli kontrak dan keturunannya itu tak mau meneruskan seni pertunjukan itu. “Dalam mengangkat kembali Ketoprak Dor yang paling sulit adalah memulihkan rasa trauma yang pernah mereka alami,” jelas Yono yang dalam 10 tahun terakhir berupaya menghidupkan kembali seni tradisi ini. Hasilnya, sejak 2015 dua grup binaannya, yakni LMARS di Medan dan Langen Setia Budi Sentosa di Deli Serdang mulai sering naik pentas.Minggu, 10 Sep 2017 11:07 WIB
Ketoprak Dor Gabungan Musik Tari dan Lakon Tradisi Etnis Jawa-Sumatera

Pertunjukan Ketoprak Dor merupakan seni pertunjukan yang menggabungkan musik, tari dan lakon
| Editor | : | Wen |
| Sumber | : | medanbisnis |
| Kategori | : | Sumatera Utara, Medan, Umum |