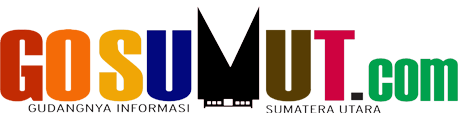Lelaki itu kemudian mengenalkan diri sebagai sikerei, sosok saman yang secara tradisional memegang posisi penting dalam pengobatan, ritual pembangunan rumah, pembuatan sampan, pembukaan ladang, kelahiran, hingga kematian. ”Nama saya Amandoji Saruruk. Masih 41 tahun, belum bertato,” ujarnya sambil tersenyum.
Berikutnya dia berpose menunggu difoto, seperti terbiasa meladeni tamu. ”Mau lihat rumah saya juga?” katanya dengan ramah.
Kami pun segera mengikutinya menyusuri jalanan beton yang membelah Dusun Ugai, Desa Madobak, Kecamatan Siberut Selatan, Mentawai. Rumah-rumah kayu berjajar. Antena parabola menyembul di halaman rumah yang ditumbuhi keladi.
Di tangga kayu rumah panggungnya, sekali lagi Amandoji berpose sebelum mengajak kami masuk. Puluhan tengkorak binatang digantung di atas pintu rumah, khas rumah penutur Austronesia.
Suasana rumah kayu itu temaram. Aneka perabotan dan pakaian digantung di dinding rumah. Amandoji menurunkan kotak persegi yang terbuat dari pelepah sagu. ”Ini tempat peralatan sikerei,” katanya.
Sesekali Amandoji bergerak liar sengaja mengagetkan, dan begitu kami terkejut, dia pun tertawa lepas. Sesaat sebelum kami berpamitan sore itu, Amandoji menawarkan diri untuk menampilkan tari-tarian Mentawai. ”Saya bisa ajak dua sikerei lain dan para penabuh gendang. Tapi, ada biayanya,” ujarnya malu-malu.
Amandoji menyebut sejumlah angka, yang menurut dia biasa dibayarkan para turis. ”Tetapi, malam ini bayarnya bisa dipotong separuhnya karena Bapak-Ibu tamu di desa ini.”
Maka, malam itu, kami pun menikmati tari-tarian Mentawai yang dibawakan Amandoji, Tesungi Saruruk (45), dan Tepoli Sararate (45) diiringi tabuhan gendang dan sesekali nyanyian.
Kebanyakan tarian itu mengisahkan perilaku alam, khususnya binatang, seperti tarian bilok (siamang), burung elang, burung hantu, dan ular. Setiap jeda, Amandoji menerangkan maksud tarian itu, sementara dua sikerei menimpalinya.
Hampir tengah malam. Hujan mereda. Kami pun pamitan. ”Semuanya berubah cepat di Mentawai, termasuk di Ugai ini. Pertama ke sini tak ada jalan beton, hanya tanah yang diapit kebun keladi. Rumah-rumahnya asli, tetapi sekarang banyak rumah bantuan pemerintah,” kata ahli genetika Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Herawati Sudoyo-Supolo, dalam perjalanan menuju rumah Aingemanai Samanggeak (41), guru sekolah dasar di Ugai yang menjadi tuan rumah kami.
Perubahan tak hanya pada fisik. ”Dulu, saat jalan bareng dengan Pater Pio—misionaris Katolik yang puluhan tahun bertugas di Mentawai—kami akan dimarahi jika memberi uang untuk pertunjukan budaya seperti ini karena dinilai merusak mental masyarakat. Tetapi, mau bagaimana lagi? Sekarang telah berubah.”
Herawati datang ke Ugai pertama kali pada 2003 dan kembali lagi ke dusun yang mesti ditempuh empat jam dengan berperahu menyusuri Sungai Rereket dari Muara Siberut itu pada 2007. Berikutnya, dia kembali ke Ugai pada minggu kedua April 2016. Semua perjalanannya itu dalam rangka survei dan pengambilan sampel genetika, selain untuk pemeriksaan kesehatan.
Penelitian genetika yang dilakukan selama 12 tahun ini telah menemukan struktur gen masyarakat Mentawai yang berbeda dengan masyarakat Nusantara lain. Struktur genetika populasi di Mentawai ternyata terendah atau bisa dikatakan minim campurannya.
Data ini memberi kemungkinan bahwa populasi Mentawai telah terisolasi sejak datang ke kepulauan yang berada di tengah Samudra Hindia itu sehingga minim percampuran dengan populasi lain.
Uniknya, tipe genetika Mentawai itu mirip dengan leluhur orang Formosa di Taiwan. Meski diketahui genetikanya mirip dengan orang Formosa, belum diketahui rute migrasinya.
Apakah mereka berasal dari Formosa atau sebaliknya? Atau apakah nenek moyang orang Mentawai dan Taiwan ini pernah tinggal di suatu tempat yang sama sebelum kemudian berpisah: yang satu menuju utara dan satu kelompok ke selatan. Untuk alasan-alasan itulah, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman kembali mengambil sampel genetika di Kepulauan Mentawai.
Tim riset yang terdiri dari ahli genetik dan antropolog ini juga menemukan perubahan pola hidup masyarakat Mentawai. Perubahan terutama terjadi pada pola makan dari sagu dan talas ke beras, yang kemudian memicu munculnya aneka penyakit non-infeksi, seperti diabetes dan hipertensi, bahkan kanker.
Keaslian dan perubahan
Genap sepekan kami berkeliling Mentawai, dari Tua Pejat di Pulau Sipora, lalu menyeberang ke Peipei di sebelah barat daya Pulau Siberut, sebelum kemudian menyusuri Sungai Rereket menuju pedalaman Ugai itu.
Sepanjang perjalanan kami disuguhi elok pemandangan. Langit dan laut yang biru dan menjingga begitu senja. Orang-orangnya pun bersahabat sehingga memudahkan pengambilan sampel.
Namun, soal makanan dan adat istiadat, memang tak gampang lagi menemukan wajah asli Mentawai. Baru setelah di Ugai itulah kami menikmati jamuan sagu, pisang, dan ikan yang dimasak di dalam bambu. Itu pun setelah kami memesannya karena tuan rumah sebenarnya menyiapkan nasi.
Sejak beberapa tahun terakhir beras Bulog deras menggelontor hingga pedalaman Mentawai. ”Anak-anak sekarang bisa tidak mau makan kalau tidak diberi nasi,” ujar Aingemanai.
”Perubahan di Mentawai memang tak terelakkan lagi,” kata Juniator Tulius, antropolog lulusan Universitas Leiden kelahiran Saibi, Siberut Tengah, yang menyertai perjalanan.
Perubahan sosial itu secara drastis terjadi sejak 1954. ”Pada tahun itu, orang Mentawai yang sebelumnya tinggal di uma di dalam hutan dipaksa menetap di kampung. Polisi dan tentara melarang ritual sabulungan, termasuk larangan lelaki memanjangkan rambut. Warga lalu dipaksa memeluk salah satu agama resmi pemerintah. Sikerei yang menolak aturan itu dipenjara,” kisahnya.
Kejadian itu berlangsung puluhan tahun, bahkan semakin menguat di era Orde Baru dengan program ”pengentasan masyarakat tertinggal dan pedalaman”. Arus balik mulai terjadi sejak tahun 1980-an ketika turis luar negeri mulai berdatangan ke Mentawai. Para turis ini awalnya datang karena terpesona laporan para antropolog Barat, seperti Reimar Schefold yang menulis tentang ”keaslian” orang Sakuddei yang tinggal di hulu Sungai Sagulubbe. Mereka lari dari Sungai Rereket karena menolak dipaksa meninggalkan kerei (sikerei) dan sabulungan. Imajinasi Barat tentang suku asli yang bertahan dengan tradisinya masih terus dicitrakan hingga saat ini. Esai foto Theguardian.com, media berbasis di Inggris, pada 5 Februari 2016,misalnya, menampilkan adegan orang-orang Mentawai di Sungai Rereket dengan naungan hutan hujan tropis nan eksotis—tentu tanpa foto jalan beton dan rumah-rumah bantuan pemerintah. Imajinasi keaslian ini rupanya juga memengaruhi sebagian orang Mentawai yang rindu kembali pada adat lama. Apalagi, setelah Orde Baru runtuh, gerakan adat di Nusantara menguat. Namun, keterputusan generasi dan pengetahuan membuat upaya kembali tidak mudah. Tulius mencontohkan tradisi bertato yang kerap disalahtafsirkan. ”Tato adalah pelindung jiwa orang Mentawai dari kekuatan jahat. Namun, sekarang banyak yang tidak melakukannya karena tidak paham, termasuk juga sikerei,” ujarnya. Saat ini, kata Tulius, orang Mentawai ibarat di persimpangan jalan. Apakah akan kembali pada identitas tradisional yang semakin kabur atau mencoba identitas modern yang tak kalah samar. Ironi itu terlihat jelas ketika kami menemui seorang kerei paruh baya yang tergeletak lemah di Puskesmas Taileleu, Mentawai Barat Daya, sambil mengeluhkan sakit lambung dan pernapasan yang dideritanya.... (ahmad arif/kompas).***