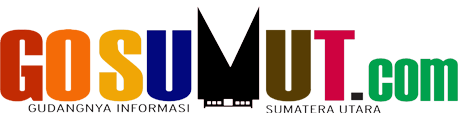JAKARTAAustralia menghadapi krisis ekologi menyusul fenomena kejadian luar biasa yang terjadi belakangan ini. Kematian jutaan ekor ikan di sungai Murray-Darling dan kematian ribuan ekor sapi ternak di Australia Barat menjadi sinyal adanya persoalan lingkungan di negara itu.
Meski pihak berwenang Australia berkilah kematian jutaan ekor ikan di New South Wales adalah dampak dari kekeringan yang berkepanjangan. Namun penduduk setempat dan akademisi menyatakan kejadian itu akibat eksploitasi air berlebihan.
Selama bertahun-tahun sebelumnya, para ilmuwan kerap memperingatkan tindakan mengekstraksi air sungai dalam volume besar tanpa memeriksa irigasi atau kegunaan lainnya. Langkah tersebut menguntungkan pengusaha karena memangkas investasi senilai miliaran dolar.
“Kematian ikan dan kondisi sungai yang sekarat bukan hanya karena kekeringan. Hal itu disebabkan praktik pengambilan air sungai secara berlebihan,” kritik pakar ekonomi air dari Australian National University, John Williams seperti dikutip AFP.
Kondisi yang terjadi di Australia ini jelas membutuhkan perhatian khusus para ilmuwan dan peneliti Australia. Meski demikian, peneliti Australia dari Universitas James Cook, William Laurance, malah sibuk menyoroti pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan di Indonesia.
Di Australia Barat ratusan ekor sapi ternak ditemukan mati dan ribuan lainnya diyakini berisiko mati akibat cuaca ekstrem. Ancaman kematian ternak juga terjadi negara bagian Queensland. Hujan yang tiba-tiba datang terus-menerus setelah kekeringan bertahun-tahun menimbulkan banjir lumpur yang menghalangi mobilitas ternak. Kelompok lobi pertanian Australia, AgForce menyatakan, diperkirakan 300 ribu ekor ternak mati, tenggelam, atau hanyut akibat fenomena itu.
Menanggapi fenomena tersebut, Guru Besar Ekologi dan Manajemen Satwa Liar IPB Profesor Ani Mardiastuti menyatakan, Indonesia bisa belajar dari kasus ini. Kematian jutaan ikan akan dipengaruhi banyak faktor. Selain perubahan iklim, kondisi sungai yang menjadi habitatnya akan ikut menentukan.
“Perlu diteliti lebih lanjut bagaimana kondisi sungainya,” katanya melalui pesan tertulis yang diterima Jumat (15/2/2019).
Soal perubahan iklim, Ani menjelaskan, Indonesia telah mengambil banyak langkah progresif untuk mengendalikannya. Di antara kebijakannya adalah perbaikan pengelolaan gambut dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
“Indonesia punya kebijakan yang kuat. Tapi implementasinya juga harus diperkuat,” katanya.
Sebagai gambaran, dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2018-2027, kontribusi EBT dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik ditarget naik mencapai 23% pada tahun 2025. Sementara, catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bauran energi pembangkitan listrik pada tahun 2017 lalu kontribusi EBT tercatat sebesar 12,52%.
Ani menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam kebijakan pengendalian perubahan iklim untuk memberi kepastian bagi pengembang energi terbarukan. Dia memberi contoh, di masa lalu pemerintah coba mengembangkan energi terbarukan berbasis jarak pagar. Namun kemudian kebijakan tersebut tenggelam. Padahal sudah ada industri yang menanamkan investasi di sana.
“Perlu kebijakan yang konsisten sehingga investasi yang ditanam ada kepastian,” katanya.
Salah satu proyek energi terbarukan yang menjanjikan pasokan listrik sebesar 510 MW ada di Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kendati bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, namun program ini direcoki para peneliti asing, termasuk William Laurance. Melalui lembaga yang dinamakan Alliance of Leading Environmental Researchers & Thinkers (ALERT), Laurance kerap menyebar tudingan tanpa bukti, dan membawa-bawa nama peneliti Indonesia dalam tudingan itu, termasuk dari Universitas Sumatera Utara (USU). Lembaga ini juga memprotes hampir semua proyek infrastruktur yang sedang digencarkan di Papua dan Kalimantan.*
Jum'at, 15 Feb 2019 15:13 WIB
Sibuk Protes Infrastruktur Indonesia
Peneliti Australia Abaikan Krisis Ekologi Negerinya

Ilutrasi saudaraperempuan.Com
| Editor | : | Sisie |
| Kategori | : | Pemerintahan, Bisnis, Hukrim, Peristiwa, Umum, Gonews Group |