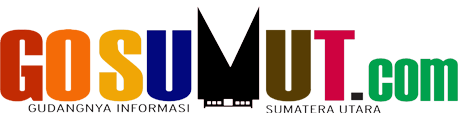Rasa jiwanya berpacu dengan nafas. Waktu pun mengipasinya untuk menginjakkan kaki di stasiun Bandung. Macet kendaraan membuat degup jantung semakin cepat. Memompa begitu cepat arteri di dalam darahnya.
Kondisi yang membuat drama itu terjadi. Ia harus menyelesaikan beberapa tugas sebelum berangkat ke lain propinsi. Tapi, hati itu gundah. Secepat waktu berlallu, secepat itu pula jantungnya berpacu memompakan darah untuk memenuhi ruang alirannya. Irama dalam memorinya seperti gelombang yang saling berkejaran. Drama itu terjadi. Menghempaskan gelora cemasnya. Menyatu dalam pelita yang seakan berdegup. “Tuhan, jangan dulu!” Batinnya berkecamuk.
Kereta datang. Langkahnya panjang menyusuri gerbong. Menghempaskan tubuhnya dalam remang harap. Pikirannya menjalar, menyusuri ketakutan-ketakutan yang akan ia hadapi.
Darah, nanah, jijik memuakkan. Memalukan! Aroma-aroma itu keluar begitu saja, menggelitik hidungnya untuk segera ditutup dengan jemari lentiknya. Anak itu telah bermandikan nanah. Hampir saja ia muntah memegangi perutnya yang seperti diaduk rasa. Rasa jijik. Tidak ada rasa jijik itu jika ia tidak menyaksikan perselingkuhan besar. Berbuah permainan yang telah menyepelekan pengorbanan jiwanya. Permainan yang mentertawakan ketidakadaan waktunya untuk sekedar memanjakan jiwa.
Saat itulah, yang ia rasakan hanya jijik. Andai saja anyir nanah itu dijilati lalat, sungguh, ia tidak mampu lagi menutupi hidungnya karena anyir itu telah menembus tulang hidungnya. Menggeltik laringnya.memburu mencari paru-paru dalam tubuhnya dan bersemayam di sana. Sugguh, ia tidak bisa menahannya.
Kereta terus mengejar waktu. Mencabik ketenangan, mencemari udara. Gemuruh roda besi itu terus saja berkejaran. “Tuhan, jangan dulu!”
Tarikan nafasnya berat. Semakin berat. Jemarinya gemetar. Telapak tanganya basah. Satu persatu kristal cair itu tumpah. Ia merasakan dalam pejaman mata. Bibirnya ikut dalam melantunkan kata, “Tuhan, beri waktu!”
Sungguh, kalau saja waktu tidak memihak ketidakadilan, ia berjanji akan melepaskan rutinitasnya demi damai jiwanya. Ia akan menemani denting hatinya, bermuara pada kasih yang sudah dipatrinya dalam sebuah sumpah.
“Sungguh, Tuhan, semuanya demi pengorbanan sebuah kewajibn untuk memberikan kesentosaan buat sesama. Untuk meletakkan keyakinan pada jiwa-jiwa yang berharap akan keadilan. Tidak lebih.”
Kristal itu semakin tumpah. Tak peduli sekitar yang terus saja memandang penuh tanya, “Ada apakah?” Buncahan rasa yang selama ini tertahan dinding baja, tak kuasa meledak. Membebaskan syarafnya menggulirkan tumpah rasa. Menyediakan sebuah telaga untuk diisi pilu. Kereta terus saja membawanya pada sebuah janji.
Sekali lagi, luapan jijik tak tertahankan saat melihat pertempuran hebat sebuah rasa yang memuntahkan muak. Meledakkan dentuman amarah yang tak terperi. Namun, semuanya seakan tertahan demi sebuah sumpah.
Bau busuk itu tak bisa lagi dibendungnya. Ingin meneriakkan kata yang mampu menembus jiwa yang tak ingin diusik dalam permainan anyir nanah yang tak tertahankan. Ia mencoba... terus mencoba menembus rasa ketidakberdayaan.
“Wahai, bukankah sudah ada perjanjian? Inikah wujudnya?” Hanya bisu dinding yang didapatinya menerima saluran amarah penuh murka. Tak ada rasa yang bisa dipagutnyademi mengokohkan teriakn sanubarinya. Terus saja ia meledak-ledak dalam ketidakmampuan menciptakan kesadaran.
“Wahai, hentikan karena ini sudah gila!”
Gemuruh roda besi terus mengejar harapnya pada rasa tak damai walau citanya mencoba mempengaruhi ruang harap. Harap bagi semua mata yang polos saat memandangnya melangkah di jalan setapak. Cipratan air yang terhantam sepatu boots hitamnya membelah becekan tanah yang masih basah ditumpahi hujan semalaman.
Puluhan kepala bergerombol dari baik jendela menyaksikan isi tasnya yang dikeluarkan satu persatu. Kamera, buku catatan, pensil, pulpen, peta, alat perekam suara, teropong, dan beberapa lainnya yang ia butuhkan selama berasa di pedalaman. Perjalanan melelahkan. Lepas dari kereta, naik angkutan umum dua jam. Naik ojeg setengah jam. Dan berjalankaki sepuluh kilo.
Terkadang jiwanya mencoba untuk terus bertanya, “Untuk apa semua ini? Tidakkah ini sudah gila?” Tapi ia tak hendak menghentikan semuanya itu. Pengorbanan untuk sesama tak ubahnya kebahagiaan bagi dirinya. Kebahagiaan? Benarkah? Bagaimana dengan kebahagiaan denting-denting hati yang ingin terus bersamanya dalam peraduan rindu? Lalu, siapa yang salah jika pengkhianatan terbesar itu menghempaskan semua mimpi indahnya dalam damai?
“Semua salahmu!” Suara itu tak henti mengusik. Bahkan tak kenal waktu. Saat ia duduk, saat ia berdiri, saatia tidur, bahkan saat ia menunduk pasrah pada keagungan asma Pencipta.
“Semua ini terpaksa ku lakukan karena ketidaksanggupan melihat penderitaan yang lebih besar menimpa alam ini. Pencemaran, kebakaran hutan, penebangan kiar, atau apapunlah namanya, semuaya berpotensi merusak karya Yang Maha Agung. Bukankah merupakan kewajiba bag manusia yang punya kesadaran penuh untuk melindunginya dari tangan-tangan dan jiwa-jiwa tak peduli?”
“Lantas, kewajiban siapa untuk mempertahankan ucap sumpah yang terikat erat? Bahkan tak ada yang bisa melepaskannya selain kematian?” Suara itu mulai memburu.
“Aku hanya mohon pengertian untuk semua itu. Pikiran dan jiwa ku tak tenang jika semua kerusakan itu terus berlanjut.”
“Pikiran dan jiwaku juga tak tenang jika mutiara hati ku lepas begitu saja meninggalkan luka bagi kebahagiaan ini.”
“Aku menyadari semua itu. Tapi ku mohon pengertian untuk semua ini. Tolong bebaskan aku untuk melakukan kebaikan ini.” Kepalanya tertunduk.
“Silahkan, tapi jangan pernah ada penyesalan jika kebahagiaan ini tercoreng, karena semua atas keinginanmu semata.”
Matanya tak juga terpejam. Kecamuk pikiran terus menggelayut mempermainkan keteguhan hatinya untuk bertahan di lebat belantara. Di luar, udara dingin terus memagut malam. Barak yang dijadikan posko itu remang-remang ditemani lampu badai dan beberapa obor yang sengaja dipasang di beberapa titik.
Bahkan kobaran api unggun yang dibiarkan terus menyala, sengaja tak dipadamkan untuk menakut-nakuti hewan liar hutan. Matanya tak juga terpejam. Telinganya semakin tajam menangkap suara-suara hewan hutan. Dicobanya membaca sebuah kitab bersampul hitam. Suaranya pelan. Mungkin ketenangan jiwa sudah mulai menjalari pori kehidupan batinnya. Pelan, rasa mulai tergambar jelas dari lebaran mulutnya yang sering terbuka.
“Kenapa kau lakukan itu? Jiwa kita ak hendak lepas karena kita percaya sebuah sumpah. Tapi kau terus saja berupaya melencengkan semuanya. Bahkan sekedar membagi kecerian semyum tak kau lakukan. Begitu tidak berartikah pengharapan itu?”
“Jangan mulai lagi menggangguku. Hanya sedikit waktu ku minta agar aku bisa konsentrasi dengan harapan semua manusia.”
“Lalu, bagaimana dengan harapanku? Tak ingin ku biarkan janji itu lepas begitu saja. Aku ...”
“Kau tak bermaksud melepaskan aku, kan? Ku mohon, ku mohon sedikit pengertian itu dari rasa kasihmu yang terdalam. Mestinya apa yang ku lakukan ini menoreh kebahagiaan bagi mu. Permatamu, seorang aktivis lingkungan yang punya rasa kepdulian untuk semua, berupaya keras memperjuangkan kelestarian alam, tak akan pernah membiarkan tangan-tangan serakah tak berperi meruntuhkan kekokohan alam karena di sana sumber kehidupan untuk semua.” Asumsinya terus saja diperkuat.
“Kalau begitu, aku sudah tidak punya harapan lagi. Niat itu begitu teguh kau simpandan tak bergeming oleh pengharapan ku ini. Kau tahu ... satu tahun itu lama. Bagaimana dengan penungguan ku? Selama masa itu kau tak akan pernah menghubungiku sekedar bertanya kabarku, makan ku, joging ku, teh manis ku, bahkan kau tak pernah mempertanyakan si manis kesayanganmu. Lalu aku harus menelan duka itu sendiri. Ini sungguh tidak adil! Kau teramat kejam!”
Bulir matanya terus menetes menemani kepiluan rasa yang berusaha dipertahankannya. Rasanya mulai hampa, seakan tak ada lagi harapan cerah menanti rindunya. Tak mampu dirinya melupakan semua peristiwa yang membelenggu sumpahnya untuk tetap bertahan. Hatinya tak juga mampu meluluhkan rasa ketidakmampuan untuk menantinya melepas kepenatan. Dirinya hanya bisa memohon suatu harap, “Tuhan, tolong beri waktu!”