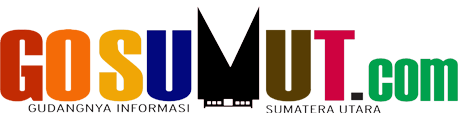ELANG adalah satu makhluk yang menjadi simbol pada banyak kebudayaan dunia. Sosoknya hadir dalam banyak mitologi. Orang Aztec di Mexico melambangkan elang sebagai wujud Dewa Matahari di bumi. Dalam Mitologi Yunani, seekor elang raksasa adalah hewan yang melayani, menemani, dan menjadi penyampai pesan Dewa Zeus.
Dalam kebudaayaan Celtic, elang dipercaya sebagai salah satu hewan tertua dan bijaksana dan seluruh makhluk. Sementara garuda adalah sosok elang yang menjadi tunggangan Dewa Wishnu dalam tradisi Hindu. Bagi orang Indian, mahkota bulu-bulu sayap elang hanya dibumbankan kepada para pahlawan sebagai simbol keberanian. Kita juga menemukan sosok elang yang menyelamatkan Gandalf dalam mitologi Skandinavia The Lord of Ring yang dituliskan oleh J.R.R. Tolkien.
Dheni Kurnia
Itulah beberapa untuk menyebut sebagian dari banyak mitologi yang mengistimewakan sosok burung elang. Pada sebagian besar jika tidak seluruhnya elang digambarkan dengan serangkaian kelebihan dan julukan: elang adalah penguasa langit, singa angkasa, satu-satunya burung dengan ketajaman mata yang bisa bertatapan langsung dengan matahari, makhluk yang tak banyak bunyi karena itu kuliknya adalah pertanda kelahiran seorang pemimpin atau mangkatnya seorang besar.
Nun di pedalaman Riau dan Jambi, di suku Anakdalam, yaitu suku Kubu di Jambi, dan Talangmamak di Riau, "tersembunyi" dan hidup juga satu mitologi atau kepercayaan pada keistimewaan sosok burung elang. "Tersembunyi" ini mungkin hanya ekspresi keterkejutan saya, karena saya memang belum pernah mengetahuinya sampai saya membaca buku puisi penyair Dheni Kurnia "Olang 2" (Palagan Press, Pekanbaru, 2016).
Bagi suku Talang Mamak, sebagaimana dijelaskan Dheni Kurnia pada pengantar buku puisinya ini, elang adalah makhluk sakral yang pantang dipelihara, diburu, ditangkap, apatah lagi dibunuh. Elang dianggap sebagai pengantar pesan kepada yang gaib, dan perantara dengan ruh leluhur. Ada tafsir yang berbeda ketika mereka mendengar elang berkulik malam atau dinihari. Dan Rajo Olang, diyakini mampu terbang menembus langit.
Dalam diri Dheni mengalir darah Talangmamak lewat kakek dari ibunya. Kesadaran akan hal itulah yang tampaknya membuat dia dekat dan sangat menguasai mitologi elang itu dan ketika dia menulis sajak maka ia mengambil, mengolah, menjadikan elang sebagai simbol pengucapan juga bahan untuk diucapkan dalam sajak-sajaknya.
Saya ingin mengatakan Dheni Kurnia adalah penyair Indonesia mutakhir yang sangat dan paling terobsesi dengan sosok elang. Kita bisa lihat dalam sajak-sajaknya di buku "Olang 2" ini. Kita bisa menemukan elang pada separuh lebih dari 85 sajaknya di buku ini.
Bagaimanakah kita harus melihat sosok Dheni sebagai penyair? Dan bagaimana penyair Dheni menghadirkan elang dalam sajak-sajaknya?
Terus-terang saja nama Dheni Kurnia sebagai penyair di Riau tidak serta-merta masuk dalam pengetahuan saya tentang kepenyairan di Riau. Ketika mulai masuk ke rumah budaya Melayu di Riau dan Kepulauan Riau, akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an saya berhadapan dan terpesona dengan nama-nama besar: Idrus Tintin, Hasan Junus, Ediruslan Pe Amanriza, Rida K Liamsi, Taufiq Ikram Jamil, Fakhrunnas MA Jabbar, A. Aries Abeba, Husnizar Hood, dan di luar itu tentu saja Sutardji Calzoum Bachri; atau nama-nama penulis muda yang pada waktu itu mulai bangkit: Syaukani Al-Karim, Ramon Damora, Marhalim Zaini, Harry B Koriun, Hang Kafrawi, Kunni Masrohanti, atau Murpasaulian.
Dalam beberapa perhelatan sastra yang saya hadiri di Riau dan Kepulauan Riau nama-nama tadilah yang saya temui. Dheni Kurnia, sekali lagi, pada tahun-tahun awal itu tidak masuk dalam perbendaharaan saya tentang penyair Riau. Jika ditilik pada usia, lelaki yang tahun ini berusia 55 tahun jelas jauh lebih senior daripada saya dan kawan-kawan yang pada tahun 2000-an awal kala itu masih menjadi satrawan muda di Riau dan Kepulauan Riau.
Respek pertama saya pada Dheni Kurnia adalah perihal ini: dia rupanya pada awal 2000-an itu beredar sebagai jurnalis di Jambi, Palembang lalu Jakarta dan ternyata di manapun ia berada, ia menyair, menulis puisi, dan menerbitkan buku puisi. Itu sebabnya saya yang dalam rangka belajar, maka saya asyik sekali mengamati perkembangan kepenyairan di Riau, tak menemukan Dheni Kurnia.
Ketika namanya saya dengar pun bukan sebagai penyair, tapi sebagai Ketua PWI Riau, amanah organisasi profesi jurnalis yang kemudian ia pegang dua periode. Sekali lagi, itu tak terkait pada sastra dan sekali lagi adalah kejutan bagi saya pribadi ketika mengetahui Dheni Kurnia penulis puisi juga, dan sajak-sajaknya bagi saya sangat memikat.
"Olang 2" adalah buku puisi ketiga, yang memuat puisi-puisi baru dan puisi-puisi lama (yang ratusan bahkan mungkin ribuan) yang tak disertakan dalam dua buku puisi sebelumnya. Untuk buku ini Dheni menulis ulang sajak-sajak lamanya itu. Pernyataan bahwa ada penulisan ulang ini kita temukan di pengantar penyair dan itu menunjukkan intensitas dan kerja menyair yang serius.
Saya percaya kerja menyair adalah kerja yang boleh tidak selesai. Membaca ulang adalah tugas penyair untuk meninjau jalan yang sudah ia tempuh, tak mesti harus ada penulisan ulang setiap kali ia menapaktilasi sajak lamanya, tapi revisi di sana-sini tentu saja bukan sebuah tabu. Satu sajak Chairil Anwar ada yang kita temukan terbit dalam lima versi di lima media yang berbeda. Ini satu bukti bahwa bahkan penyair besar kita itu senantiasa gelisah, membaca lagi, dan meninjau karya-karyanya.
Saya ingin membagi sajak-sajak dalam buku ini ke dalam dua kelompok ekstrem: pertama, sajak-sajak bepergian ke jarak yang jauh, dan kedua, sajak-sajak permenungan ke diri yang dalam. Keduanya adalah perjalanan. Keduanya melibatkan kerja batiniah dan badaniah.
"Bagi saya, puisi adalah realitas. Kenyataan," ujar Dheni di awal pengantarnya di buku ini.
Saya agak tersentak dengan pernyataan yang seolah-olah antipuisi dan seakan-akan menyederhanakan tuntutan akan kompleksitas atau kepelikan dalam puisi yang baik dan kepelikan itu bagi saya adalah syarat nikmat yang harus ada dalam puisi. Benarkah Dheni menolak kompleksitas? Lalu kemudian sajak-sajaknya jatuh ke golongan sajak transparan yang habis sekali baca sebagaimana kita membaca realitas atau kenyataan di surat kabar?
Mau tak mau kita harus membaca penuh pengantarnya dan seluruh sajak-sajaknya. Lalu lewat satu-satunya jalan itu saya sampai pada kesimpulan bahwa yang dimaksud oleh penyair kita ini adalah bahan persajakannya. Ya, bagi Dheni Kurnia, (bahan terpenting bagi) sajak-sajaknya adalah realitas, kenyataan.
Dia tidak berkhayal, dia tidak mengawang-awang. Ini adalah pilihan yang cermat. Kenyataan bagi Dheni adalah apa yang ia alami dan saksikan di depan matanya. Lelaki kelahiran Airmolek, Indragiri, Riau ini misalnya tidak terpikat pada tema kekalahan sejarah dan meratapinya sebagai kemalangan pecahnya kebersatuan Kemaharajaan Melayu Raya, meskipun saya yakin sebagai lulusan FKIP Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau dia sangat menguasai bahan sejarah itu.
Apakah sejarah bukan wujud realitas bagi Dheni? Mungkin ini soal pilihan. Ia lebih memilih menggerutukan perihal bencana asap yang berulang atau leguh-legah kongres mahasiswa yang makan dana tak sedikit itu.
Disiplin Dheni pada realitas pasti karena kerja profesionalnya sebagai jurnalis yang handal. Ia pencatat yang cermat. Itu menghasilkan karya jurnalistik yang baik dan ketika ia melihat ke sebalik realitas itu maka jadilah sajak-sajak yang tebal. Sajak-sajaknya adalah reportase yang telah diperkaya, diberi garis bawah di sana-sini, dipertegas, dan ditandai dengan pendapat personalnya di berbagai bagian. Inilah modus umum kerja menyair Dheni Kurnia yang melahirkan apa yang saya kelompokkan sebagai sajak-sajak bepergian ke jarak yang jauh.
Penyair kita ini singgah ke Paris dan merenungkan Menara Eiffel, Sungai Sein, Loire; Ia melawat ke Swiss dan mencatatkan realitas yang ia tangkap di Basel dan Zurich dalam ingatannya; Ia berkunjung Singapura dan meresapi banyak detail di negeri jiran itu: stasiun, halte, lalu lalang pecandu belanja, kawasan pelancongan yang dengan kritis ia sebut sebagai negeri tak bertuhan, dan menafsir mitologi Merlion; terbang ke Brunei dan entah lewat jalan ajaib mana di sana dia justru mencatat perbandingan unik antara Cinderella dan Rabiatul Adawiyah; dan di buku ini kita diajak Dheni untuk melihat banyak tempat lain – kota-kota di Amerika, Bangkok, Tembok Besar dan Kota Terlarang di Tongkok – lewat sajak-sajaknya juga tentu saja Sungai Siak, di Riau, tanah lahir dan mastautinnya kini.
"Apa yang saya alami. Apa yang saya temukan. Apa yang saya catat. Apa yang saya lihat. Apa yang saya pendam. Apa yang saya rasakan; itulah puisi," kata Dheni.
Ini makin menegaskan bahwa yang ia maksud "kenyataan/realitas" itu adalah (bahan) puisi saya". Puisi adalah selalu tentang dua hal: mau menyampaikan apa, dan bagaimana cara menyampaikannya. Yang satu menjadi tema yang lain menjadi estetika puitika. Yang satu perihal isi yang lain mewujud jadi bentuk. Dheni punya bahan yang berlimpah untuk disajakkan.
Karena itu, sebagaimana diakuinya, ia telah menggubah ribuan puisi. Dan buku ini memuat tak sampai seratus sajak. Tak semua ia siarkan. Kenapa? "Karena, ya itu, (sajak-sajak saya itu adalah) catatan hidup saya. Catatan perjalanan pribadi saya."Terlalu merendah rasanya ketika penyair kita ini menyebut puisinya hanya untuk,"saya kenang dan dibaca-baca menjelang saya tidur”.
Sajak-sajak Dheni, memakai istilah Subagio Sastrowardoyo adalah sajak yang menjadi berarti karena telah berhasil melepaskan tautan pada diri penulisnya sendiri.
Kelompok kedua sajak-sajak dalam buku ini saya kelompokkan sebagai sajak-sajak permenungan ke diri yang dalam. Yaitu sajak-sajak yang tidak hanya meninjau diri sendiri, tapi menggarap objek elang hingga ke tulang-tulangnya. Ada serangkaian sajak yang mengupas ‘qodam elang’ dari berbagai ihwal. Ini salah satunya:
Qodam Elang, Pemburu
Kau adalah pemburu yang hebat Jarang gagal dalam setiap medan Padahal, tulangmu berlubang Sering tak seimbang dengan panjangnya kepak.
Padahal, parumu bengkok Sering mencabuti bulu sendiri Tapi kau tak pernah lupa dalam mengejar Karena piawai membelah udara Dan berani menentang angin.
Pekanbaru, 90.15/16
Ada 52 sajak yang nyaris tuntas mengupas tema elang, dari sosok elang itu sendiri (Di tubuh elang bermukim qodam/ Di qodam elang, menyipay tubuh), mata elang (Tajam matamu di cahaya siang.
Agar kau bisa memandang dunia tanpa tengadah), kepak elang (Aku bergantung di kepakmu / Yang panjang menembus langit), paruh elang (Mengatakan yang benar adalah dia / Mengatakan yang salah tanpa jeda), begitulah, kuku, kutu, lidah, dada, gerak berputar, membumbung, menukik, suara kulik, semuanya digarap dengan intensitas yang sama dalamnya, semua termakna, atau menjadi alat ucap untuk menyampaikan pesan.
Pada rangkaian sajak serial "Qodam Elang" inilah konteks mantra puisi (yang disebutkan pada judul) itu mendapat tempat. Serial sajak ini memang terasa seperti serangkaian mantra. Tapi ini mantra untuk apa? Jika di masyrakat tradisional – mungkin di Suku Talang Mamak masih dipercaya – mantra, kata-kata 'sakti' yang tak mudah difahami maknanya dalam logika berbahasa biasa – dianggap bisa mengusir roh jahat penyebab sakit, atau sebaliknya memanggil roh halus untuk menjaga atau melakukan sesuatu, maka 'mantra elang' Dheni Kurnia itu apakah sesakti itu juga? Tentu saja tidak.
Dheni hanya mengambil model mantra untuk bentuk sajaknya. Ia ingin menghadirkan aura gaib dalam bentuk mantra itu: repetisi, pemujaan pada kelebihan sosok elang, juga diksi yang menyaran ke arah situ: Di mandi air, mandi bulian / Kau ratap air mengobat bulia.
(Qodam Elang, Bulian). Mungkin, jika sajak-sajak itu dibacakan, atau diratapkan seperti mantra orang Talak, maka orang yang mendengar dengan mudah akan berdiri bulu kuduknya. Ya, saya membayangkan ini adalah juga sajak-sajak yang auditif, ada kelebihan pada bunyi jika dilisankan.
Tapi, tak semua sajak ‘mantra’ ini berhasil sampai penuh menghadirkan aura ruap dupa seperti itu. Pada sajak akhir dalam serial “Qodam Elang’, yaitu ‘Malu’, mantra itu hanya tersisa pada bentuk. Isinya? Justru menjadi seperti pernyataan tentang kenyataan populasi dan habitat elang yang terancam.
Qodam Elang, Malu
Aku adalah elang perkasa Melesat seperti lembing Menggirik seperti mata besi Mengepak mengguru terbang.
Mencapik hingga tuntas Tapi aku malu dengan mata Malu dengan hutan tinggal lalang Malu dengan punai menyisik kepak Keperkasaanku hanya legenda.
Pekanbaru, 90.15/16.
Ada banyak sajak lain di luar serial elang tadi yang ditulis juga dengan kesadaran penuh untuk menghadirkannya sebagai memenhadirkan kembali bentuk mantra. Pada beberapa sajak, Dheni tampaknya tak ada pilihan kecuali memakai kata-kata asli suku Talangmamak, yaitu ketika ia menulis beberapa sajak naratif tentang Suku Tuha, nama lain suku Talang Mamak.
Suasana dan kesan bahkan pesan yang ingin dibangun tak akan sampai dengan utuh jika kata-kata asli itu disingkirkan. Tetapi saya tak menemukan alasan kenapa Dheni memilih kata "malaykat" atau "ketederal", bentuk yang tidak baku dari kata “malaikat” dan “katedral”, pada beberapa sajaknya.
Bagi saya buku ini adalah pembuktian kepenyairan Dheni Kurnia, ke luar ia adalah pengamat realitas, pencatat dan penafsir realitas yang cermat nan kritis, ke dalam ia penilik perasaan, dan penggali pernik-pernik tradisi yang jeli dan tekun. Hasilnya adalah sajak-sajak dengan struktur kuat, interior yang pada beberapa sajak terasa berlebihan tapi tak sampai terlalu mengganggu, dan diucapkan dengan sangat lancar.
Satu hal lagi: dengan darah Talang mengalir di tubuhnya, Dheni Kurnia telah menjadi juru bicara yang lantang bagi kegelisahan Suku Talang Mamak lewat sajak-sajaknya, sebagai mana disebutkan kritikus Maman S Mahayana, dalam tulisannya mengantar buku ini dan saya setuju. Ini adalah sebuah pilihan strategi menyair yang tak dibuat-buat. Akhirnyq.
"Dalam konteks perpuisian Indonesia, puisi-puisi Dheni Kurnia betul-betul lepas dari mainstream perpuisian kita yang cenderung berkutat pada problem aku lirik yang dikepung kehidupan masyarakat sekitar," ujar Maman lagi, dan lagi-lagi saya setuju. ***
Jum'at, 10 Feb 2017 11:08 WIB
Pembacaan atas Sajak-sajak Dheni Kurnia "Olang 2"
Ulasan Buku: Elang di Talang Mamak, Singapura, New York, Paris, hingga Madinah

Penyair dan Jurnalis asal Riau, Dheni Kurnia saat tampil membawakan karya puisinya. (dok. Dheni Kurnia)
| Editor | : | Muslikhin Effendy |
| Kategori | : | Gonews Group |