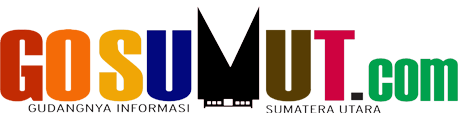MARI kita andaikan UU Pers tak ada lagi. Beberapa media mungkin menjadi korban karena bekerja tanpa perlindungan. Tapi setidaknya kita memperkecil ruang bagi industri media partisan untuk bersembunyi di balik ''kebebasan pers''.
Sekarang kita andaikan Dewan Pers yang dibubarkan. Beberapa jurnalis barangkali langsung dipenjara karena tak ada lagi mekanisme mediasi. Tapi dengan bubarnya Dewan Pers, setidaknya kita menutup peluang sertifikasi profesi dipakai sebagai kedok formal agar para wartawan dapat leluasa menembus sumber-sumber iklan atau menegoisiasikan kontrak halaman di sela-sela sesi wawancara.
Atau sebaiknya Kode Etik saja yang dihapus, dan perilaku media diserahkan kepada kebijakan masing-masing ruang redaksi. Hal terburuk yang akan terjadi barangkali sebuah konflik sosial atau bahkan genosida, seperti kebohongan yang disebar media tentang penganiayaan dan mutilasi tujuh Pahlawan Revolusi tahun 1965. Dan ini hal serius.
Tapi tanpa Kode Etik, setidaknya media tak perlu repot-repot mencantumkan “wartawan kami tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun”, namun di saat yang sama, mereka dengan sadar menginjak-injak pagar api dengan pertimbangan perolehan iklan atau kepentingan bisnis dan politik para pemegang saham.
Entah dengan Anda, tapi lima tahun terakhir ini, saya merasa lebih takut melanggar community standard-nya Facebook atau Twitter, daripada Kode Etik Jurnalistik. Sanksi dari Facebook atau Twitter beruapa penutupan akun, nyaris setara dengan kematian perdata bagi sebagian orang. Tapi melanggar Kode Etik atau Pedoman Perilaku Penyiaran, paling hanya menerima selembar surat dari Komisi Penyiaran Indonesia dan meski surat itu datang setiap hari selama 10 tahun, toh izin frekuensinya tetap akan diperpanjang.
Jadi siapa bilang kepentingan publik hanya dijaga oleh kode etik atau P3SPS? Dua set aturan yang dapat dihafalkan dalam dua atau tiga malam menjelang ujian kompetensi wartawan.
Menjelang Pemilu 2014, di Gedung Dewan Pers, saya menjawab sebuah tantangan debat terbuka melawan sederet pejabat redaksi sebuah grup media yang kebijakan redaksinya dapat saya buktikan partisan. Tapi pada pemilu kali ini, pemilik group media yang sama telah berpindah afiliasi politik. Lalu mereka yang pernah hadir membela korporasinya dalam debat itu, kini menjadi penguji untuk sertifikasi wartawan, di mana salah satu materi yang diujikan adalah tentang independensi.
Atau bagaimana jika kita andaikan organisasi profesi atau serikat pekerja media dilikuidasi saja. Yang ini tampaknya lebih realistis. Selain karena jumlahnya terbatas, perannya juga tak terlalu signifikan. Bahkan kerap membenani batin anggotanya yang dihadapkan pada pilihan antara setia dengan nilai-nilai organisasi atau menghadapi tekanan perusahaan tempatnya mencari nafkah untuk keluarga.
Apalagi, di pintu gerbang revolusi industri keempat ini, tak ada tempat untuk meromantisasi kisah buruh-buruh media yang sok idealis. Kecerdasan buatan dalam jurnalisme tak akan pernah berkhianat dibanding kecerdasan organik para wartawan yang memiliki agama, menyanyi lagu kebangsaan, atau terlahir sebagai suku tertentu, tetapi gagal mengelola bias-bias itu dalam memproduksi informasi.
Big data atau algoritma dari super-komputer milik perusahaan media yang baru saja diakusisi sebuah perusahaan rokok atau ojek online, jelas jauh lebih dapat diandalkan daripada laptop-laptop jurnalis yang biaya perawatannya tidak masuk sebagai komponen dalam struktur upah minimumnya.
Youval Noah Harari mengingatkan datangnya jenis manusia baru yang dimakan oleh evolusinya sendiri. Sekelompok homo sapiens yang disebutnya sebagai useless class.
Kelas ini bahkan lebih sial dari proletar dalam narasi Marxian. Useless class adalah sebuah generasi manusia yang hampir tak punya peran apa-apa dalam peradaban, karena seluruh organnya telah digantikan oleh mesin atau aplikasi. Fotografer atau camera person dengan motor kreditan yang terhalang kemacetan, kalah cepat dengan rilis gambar CCTV.
Kini berita gempa atau ancaman tsunami, tak perlu menunggu wartawan dan redakturnya karena aplikasi telah mengerjakannya secara real time.
Seni, konon adalah pertahanan terakhir manusia menghadapi mesin. Tapi semua jumawa ini runtuh ketika komputer dapat diprogram untuk mengaransemen musik atau melukis.
Useless class tak dapat bersaing dengan mesin yang telah berevolusi melampaui batas-batas fisik dan biologis para penciptanya sendiri.
Otot sapiens telah digantikan otot kuda. Otot kuda digantikan uap atau foton cahaya matahari. Itu cerita revolusi lama. Lalu mata digantikan lensa atau sensor, dan kini otak dicangkokkan pada sebuah program, sekadar untuk menstimulasinya menuju fase mandiri.
Mesin tentu akan membuat kesalahan. Tapi ia akan belajar dari kesalahan itu. Inilah artificial intelligence. Dan peluangnya untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, jauh lebih besar dari homo sapiens manapun.
Lantas siapa yang hari-hari ini masih butuh perantara pada sumber-sumber informasi? Di hadapan kuasa platform dan kekuatan mesin pencari, siapa yang masih berani mendaku sebagai pembawa pesan yang jujur, bak kisah nabi-nabi terdahulu?
Pada altar algoritma, siapa kita yang masih mengaku dapat memilih dan memlilah hal-hal yang relevan dan yang tidak bagi pembaca? Kepada rumus-rumus Search Engine Optimation atau SEO jua lah, akhirnya para redaktur bahasa mulai meratapi eksistensinya.
Apa itu news value? Apakah news peg sama dengan trending topic? Apakah headline ditentukan warna sepatu apa yang dikenakan seorang pejabat hari ini? Bagaimana dengan goyang dayung?
Apakah konten masih penting dibanding platform? Apakah editorial yang sakral masih didengar dan menembus ruang-ruang gema atau echo chamber di alam post-truth ini?
Lalu di tengah jawaban-jawaban yang serba tak pasti tentang masa depan, kita seperti ditarik oleh mesin waktu untuk membicarakan sebuah entitas sosial bernama LBH Pers. Lembaga Bantuan Hukum Pers.
Apa ini? Di mana letak dan perannya di masa depan? Lembaga Bantuan Hukum Pers. Bukankah industri atau profesi yang hendak dibantunya justru sedang samar nasibnya?
Kita berkumpul di sini karena kita dalam kesadaran penuh, masih menginjak bumi. Kejahatan terhadap pers masih dilakukan secara ''analog''. Para pelaku persekusi terhadap media masih membawa bogem dan pentungan secara offline seperti layaknya sapiens yang baru melewati revolusi kognitif.
PHK sewenang-wenang terhadap jurnalis dilakukan bukan karena dampak investasi super komputer atau keberhasilan konvergensi ruang redaksi yang membuatnya lebih efisien, tapi PHK dilakukan karena para wartawan mendirikan serikat pekerja atau mempertanyakan kebijakan kerja rangkap sebagai pencari iklan.
Di tengah zaman di mana peretasan dilombakan dan menjadi hiburan, kita masih menghadapi para serdadu yang secara manual merusak kamera dan mengincar memory card seorang fotografer atau videografer yang merekam kekerasan di luar hukum.
Lalu para perwiranya menegosiasikan perdamaian dengan petinggi redaksi dan pengacara perusahaan. Case closed. Kasus ditutup begitu saja dengan penggantian kamera yang rusak.
Semua orang senang. Tak ada yang perlu masuk penjara karena delik penghalang-halangan hak publik atas informasi.
Kita masih menginjak bumi bersama LBH Pers, karena meski Dewan Pers tak perlu dibubarkan, ia tampak kewalahan dengan munculnya indie publisher, vlogger, travel writer, atau jurnalis-jurnalis warga yang kadang bekerja jauh lebih ketat dari standar industri media, tetapi tak mendapat fasilitas advokasi dan pengakuan sebagai bagian dari ''pers nasional''.
Kita juga hadir di sini karena kita percaya, masih ada pestisida bernama Undang-Undang ITE yang tak hanya menyerang apa yang diyakini sebagai hama atau parasit dalam kebebasan informasi, juga organisme lain yang menjadi bagian dari ekosistem.
Lagipula pestisida adalah jalan pintas dalam nalar industri pertanian monokultur akibat kegagalan menjaga pengetahuan tentang biodiversity dan mempertahankan metode organik. UU ITE dalam metafora pestisida, adalah salah satu cermin kegagalan negara, sistem pendidikan, dan kita semua, dalam meningkatkan literasi atau kedewasaan organik setiap individu.
Perjuangan terhadap kebebasan berpendapat dan perkembangan teknologi informasi, tak cukup diimbangi dengan usaha-usaha membebaskan manusia dari ketergantungannya pada fiksi-fiksi yang dogmatis, yang membunuh secara perlahan kemampuannya mengembangkan critical thinking.
Dengan sederet persoalan tadi, kini kita melihat lebih jelas di mana letak entitas seperti LBH Pers pada ruang dan waktu yang sedang bergerak.
Seperti lazimnya lembaga bantuan hukum, LBH Pers diniatkan untuk membantu mereka yang tak sanggup mengakses hukum secara komersial. Di satu sisi kita melihat konsolidasi bisnis media yang semakin terkonglomerasi. Mereka lah industrial actor dalam jurnalisme.
Tapi di sisi lain, platform dan teknologi juga membaut produsen informasi menjadi semakin individual dan terdesentralisasi. Pada ceruk inilah keberadaan lembaga advokasi probono seperti LBH Pers menjadi relevan.
Ia akan hidup bersama munculnya non-industrial actor dalam produksi informasi. Ia akan menjadi katalis yang mentransformasi nilai-nilai integritas dan independensi dalam pers, menjadi sebuah norma dan adab bersama dalam berkomunikasi hingga ke level individu, pada semua jenis platform, dan pada setiap pesan yang direproduksi.
Ia tidak lahir untuk membela yang kuat. Yang ia bela adalah pers sebagai sebuah nilai dan gagasan dalam peradaban dan demokrasi. Bukan merk dagang atau individu jurnalisnya.
Ia bisa berhadapan dengan media yang memecat wartawannya secara sewenang-wenang, meski ia juga akan membela saat perusahaan media itu menghadapi tekanan aparat atau massa underbouw sebuah partai politik.
Ia akan duduk bersama para pengacara publik yang lain untuk mengugat negara dan produk hukumnya yang mengancam kebebasan berekspresi, meski tak menyangkut industri media secara langsung.
Sebaliknya, meski namanya LBH Pers, ia tak akan segan berada dalam satu barisan bersama publik mengecam pers dan para jurnalis yang partisan atau media-media tertentu yang mengancam sendi-sendi demokrasi seperti keberagaman dan toleransi dengan gagasan-gagasan sektarian.
Maka jika hari ini kita masih melihat ancaman terhadap pers hadir secara offline dan nyata dalam bentuk kekuatan otot, uang, kekuasaan, atau sektarianisme, sementara di sisi lain ancaman revolusi digital terhadap pers masih dalam bentuk proposal-proposal start up company di lembaga-lembaga venture capital, saat itulah kita masih membutuhkan LBH Pers.
Tak hanya sebagai sebuah lembaga. Terlebih sebagai sebuah gagasan yang akan tetap relevan.***
Dandhy Dwi Laksono merupakan Koordinator Majelis Pertimbangan Organisasi Aliansi Jurnalis Independen (MPO AJI) Indonesia dan pendiri Watchdoc.
* Tulisan ini merupakan orasi budaya yang disampaikan Dandhy Dwi Laksono pada Malam Penggalangan Dana LBH Pers di Goethe Jakarta, Kamis malam, 30 Agustus 2018.
Jum'at, 31 Agu 2018 15:21 WIB
Advokasi Media dan Relevansi Zaman

Dandhy Dwi Laksono